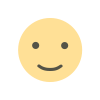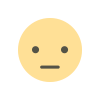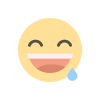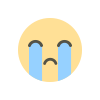Pilkada dan Biaya Politik yang Jadi Kambing Hitam
Dalam setiap pemilu di Indonesia; Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden selalu menjadi ajang untuk “mendulang dana publik" secara besar-besaran baik dengan cara halal maupun dengan cara curang. Tetapi kita selalu mencurigai (dan memang pantas dicurigai) dana kampanye yang digunakan itu (terutama oleh petahana) berasal dari praktik curang, suap-menyuap dan korupsi dana APBN maupun APBD, (dengan lompatan logis yang jauh), menyebabkan kualitas pemilu menjadi sangat rendah, akibatnya pejabat terpilih adalah orang-orang dengan kualitas rendah dan cacat intelektualitas bahkan integritas, setidaknya begitulah arus utama menilainya.

Dalam setiap pemilu di Indonesia; Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden selalu menjadi ajang untuk “mendulang dana publik" secara besar-besaran baik dengan cara halal maupun dengan cara curang. Tetapi kita selalu mencurigai (dan memang pantas dicurigai) dana kampanye yang digunakan itu (terutama oleh petahana) berasal dari praktik curang, suap-menyuap dan korupsi dana APBN maupun APBD, (dengan lompatan logis yang jauh), menyebabkan kualitas pemilu menjadi sangat rendah, akibatnya pejabat terpilih adalah orang-orang dengan kualitas rendah dan cacat intelektualitas bahkan integritas, setidaknya begitulah arus utama menilainya.
Namun demikian, rakyat yang biasanya memiliki kualitas moral alakadarnya, berhak menuntut kualitas moral dan integritas yang tinggi dari pejabat politik terpilih. Paradoksnya, para pejabat sebagai representasi dari publik adalah cerminan dari kualitas moral pemilihnya, jika pejabat yang dipilih buruk, besar kemungkinan masyarakat pemilihnya juga bermasalah. Bahwa kualitas pemilu tidak saja ditentukan oleh para kontestan, partai politik dan pemerintah, tetapi juga oleh rakyat sebagai stakeholder utama dari sistem tersebut yaitu demokrasi.
Indikator dari rendahnya kualitas hasil pemilu mudah saja dilihat secara kasat mata. Kualitas undang-undang (UU) yang dianggap sangat rendah; sarat kepentingan sesaat dari partai politik atau elitnya; banyaknya UU yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi; UU yang menimbulkan polemik; parlemen yang pemberang; anggota DPR yang hampir separuhnya selalu bolos di sidang paripurna dan tingkat kehadiran yang rendah dalam setiap sidang; kunjungan luar negeri yang tidak membawa manfaat bagi legislasi; masa reses yang tidak produktif; perseteruan dengan pemerintah yang tak berujung pangkal; komentar-komentar tak bermutu yang dilemparkan kepada publik yang membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka itu orang-orang terdidik?, dan tentu saja; yang lebih parah adalah korupsi berjamaah yang sering dilakukan oleh anggota parlemen (nasional dan daerah) dan kepala daerah dalam banyak proyek-proyek pemerintah.
Bisa kita cermati dari beberapa kali pemilu dan pilkada setelah reformasi, sistem pemilu yang dibuat rasanya sudah memadai untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan berkualitas, sistem pemantauan yang fair, pelaksana yang independen dan tidak adanya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan pemilu (setidaknya hingga kini belum ada bukti material bahwa telah terjadi intervensi tersebut.)
Kambing hitamnya sering sekali: biaya politik yang tinggi.
Mengikuti pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) membutuhkan dana besar. Elemen dana itu bisa saj mahar politik (meskipun ramai-ramai dibantah), kampanye, iklan, logistik, ongkos transportasi, mendanai even-even yang diajukan calon pemilih, sumbangan-sumbangan ke rumah ibadah dan LSM, dan ragam biaya lainnya.
Benarkah hanya politik biaya tinggi yang menjadi sebab para politisi menjadi korup (baik dalam masa kampanye atau pun selama menjabat untuk mengembalikan utang atau dana pribadi untuk biaya kampanye)?
Ada beberapa poin penting yang menyebabkan kondisi ini tumbuh dan berkembang semakin buruk, yang terjadi di dalam tubuh partai politik secara khusus dan masyarakat secara umum yang bisa menyebabkan kehancuran sistem politik kita.
Politik Tanpa Ideologi
Partai politik di Indonesia tidak dibedakan berdasarkan pilihan ideologisnya tetapi hampir semata berdasarkan kepentingan elitnya belaka. Tak ada warna ideologis yang jelas bisa kita kita sematkan kepada partai politik Indonesia, bukan saat ini saja, tetapi sejak pemilu pemilu pertamakali dilaksanakan. Pemilu 1955 diikuti oleh 172 partai untuk memperebutkan 250-an kursi DPR, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai. Di zaman Orde Baru pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik (Golkar tidak dinyatakan sebagai partai). Pada era orde Baru, kondisinya mirip sekali seperti rezim fasis di Italia dan Jerman di masa Perang Dunia II dan sistem pemerintahan komunis di China, Kuba dan Uni Soviet, di mana pemerintah melalui Golkar sebagai kendaraan politik penguasa mengontrol semua aspek politik kenegaraan.
Selepas reformasi, problema kepartaian tidak berubah. Pemilu 1999 partai peserta pemilu berjumlah 48 dan hanya 21 partai yang memenangi kursi parlemen. Berlanjut ke 2004, 24 partai. Pemilu 2009 partai peserta pemilu melonjak menjadi 38 dan turun lagi pada Pemilu 2014 dengan 12 Partai dan Pemilu 2019 akan diikuti oleh 15 partai politik dan 4 partai lokal di Aceh. Pemilu 2024, seperti yang sudah kita ketahui bersama, masih melanjutkan fenomena tersebut.
Dari sekian banyak partai politik yang ada, kita kesulitan untuk menentukan ideologi yang diusung oleh masing-masingnya. Sebagai contoh Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, Partai Berkarya, Partai Garuda sebenarnya berakar kepada induk ideologis yang sama yaitu Golkar. Partai-partai yang bercirikan religius Islam: PAN dan PKB (meskipun tidak secara resmi menyatakan diri sebagai partai Islam), PKS, PPP, PBB. PSI sebagai partai yang relatif baru bahkan tidak jelas apa akar ideologisnya. Sementara PDIP yang bercirikan nasionalis sebenarnya tak jauh berbeda pula dengan Gerindra yang mengklaim diri sebagai nasionalis.
Sehingga apa yang kita lihat dari kampannye politik parta-partai tersebut adalah: glorifikasi tokoh karena ada dinasti politik di dalamnya; program yang tak jauh berbeda karena garis ideologi yang hampir sama; remeh temeh saling serang karakter lawan politik; adu pantun dan adu keren singkatan nama pasangan calon dan yang paling meriah biasanya adalah pentas dangdutnya tanpa ada pidato politik yang bermutu yang bisa dijadikan rujukan oleh pemilih.
Jika partai-partai ini bisa disatukan berdasarkan ideologi, maka kontestan pemilu tentu semakin sedikit dan akan berimbas kepada berkurangnya biaya penyelenggaran pemilu, biaya kampanye dan politik mahar bisa diminimalisasi serendah mungkin. Apalagi jika, ideologi itu memang tuntutan dasar bagi calon yang ingin diusung oleh partai, karena ideologi biasanya menuntut idealisme dan integritas. Maka perkara mahar-maha bisa dipangkas.
Politik Inang dan Parasit
Selama ini partai politik tidak mampu menjadikan dirinya sebagai mesin politik yang efektif. Akibatnya partai politik dianggap sebagai inang bagi para elit, sebagai parasit menyangkutkan dirinya untuk mengantarkannya kepada kekuasaan. Partai politik sebagai inang ini sudah lazim sepertinya. Sebagai contoh, jika seorang tokoh tidak melihat kepentingannya diakomodasi lagi, mereka dengan mudah pindah ke partai lain yang lebih menguntungkan. Hal ini juga berkaitan dengan partai politik yang tidak lagi menjadi tempat bersemainya ideologi, tetapi hanya sebagai tempat saluran untuk memenuhi kepentingan belaka. Jika seandainya partai politik efektif sebagai sistem ideologis tentu saja praktek inang ini tidak akan mudah terjadi. Akibatnya, politisi yang dihasilkan adalah politisi yang mengejar keuntungan finansial belaka dari keterlibatannya di dalam partai politik dan kontestasi pemilu.
Rendahnya Kualitas Kader Partai
Jika tidak salah ingat, Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan: “…dan politikus tidak mengenal Multatuli, bisa menjadi politikus kejam. Pertama dia tidak kenal sejarah Indonesia, dua tidak mengenal humanitas secara modern dan (akibatnya) bisa menjadi kejam… Saya yakin para politikus sekarang tidak membaca apa-apa…”
Pernyataan Pramoedya Ananta Toer di atas bukan pernyataan kosong belaka. Banyak dari anggota parlemen kita (begitu juga kepala daerah) yang tidak memahami apa sesungguhnya tugas mereka sebagai pejabat negara. Dan itu bukan rahasia lagi. Tentu saja tidak bisa dikatakan para politisi atau calon politisi itu berpendidikan rendah, namun wawasan politik dan kurangnya minat baca bisa jadi penyebab hal itu terjadi.
Kita masih ingat Anang Hermansyah, anggota DPR dari PAN yang pernah mengatakan bahwa reses adalah waktunya untuk dia mengurus anak. Satu fakta ini tidak bisa menjadi cerminan kualitas kader-kader partai secara umum namun tetap saja sangat mencengangkan. Inilah salah satu akibat dari partai politik sering dijadikan inang saja oleh para elit dan parasit politik lainnya.
Partai politik seharusnya menjadi “kawah candradimuka” bagi kadernya. Partai politik bertugas merekrut calon-calon politisi dengan kecerdasan tinggi untuk memahami ideologi partai; meninggikan kadar idealisme dan integritas diri mereka; mengasah diksi dan keahliannya berbicara di depan publik; bagaimana mencitrakan diri secara baik sesuai dengan kualitas dirinya; belajar politik secara luas; meningkatkan wawasan dan konstelasi berpikirnya; menjadi intelektual dan praktisi sekaligus. Karena mereka akan berhadapan dengan tugas yang tidak ringan untuk melayani rakyat sebagai tugas idealnya, calon legislator dan pejabat publik.
Tetapi partai politik mengabaikan tugas utama tersebut. Akibat dari kaderisasi yang amburadul itulah, banyak partai dengan senang hati menerima orang luar sebagai caleg asal bisa menanggung biaya kampanye, karena kualitas dan popularitasnya kadernya tidak memadai. Sehingga bermunculan politisi instan dari kalangan artis, selebiritis, pelawak dan bahkan mantan koruptor asalkan mereka terkenal dan berduit.
Voluntarisme yang Belum Dimaksimalkan
Voluntarisme (bukan dalam makna filosofis) perlu menjadi solusi baru bagi Indonesia. Selama ini, sikap kesukarelaan masyarakat tidak bisa “dieksploitasi” oleh partai politik. Padahal, keterlibatan masyarakat secara sukarela bisa mengurangi biaya politik secara signifikan dibanding harus membayar seluruh staf kampanye. Sikap voluntarisme politik ini seharusnya menjadi model dalam sistem politik kita.
Partai (dan juga tokoh politik) seharusnya mampu menggugah masyarakat untuk terjun dalam kegiatan politik. Bahwa politik itu bukan kepentingan partai politik, elit dan golongan tertentu saja, tetapi merupakan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Mencitrakan bahwa “politik itu busuk” harus segera dihentikan, baik oleh tokoh politik, partai politik itu sendiri (dengan korupsinya), media massa, universitas, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat. Politik adalah milik kita bersama. Sehingga pemilu bukan masanya untuk menerima “uang sogokan” pemilihan, tetapi memang dirasakan sebagai bagian dari hajat hidupnya, berupa hak dan kewajibannya.
Dengan tumbuhnya kesadaran itu, voluntarisme dalam kontestasi politik bisa ditingkatkan. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara maju Eropa lainnya, banyak anak muda yang dengan sukarela terjun ke dalam kampanye-kampanye politik baik ditingkat kota, negara bagian maupun tingkat nasional. Banyak pula pemuda bercita-cita menjadi politisi terjun ke dalam kampanye-kampanye sebagai magang atau tenaga sukarela. Untuk mempelajari bagaimana kampanye politik diselenggarakan, menjalin jaringan dengan entitas politik dan tokoh-tokohnya dan yang terpenting, voluntarisme itu pada akhirnya juga bisa mengarah kepada pengumpulan dana publik untuk biaya kampanye, sehingga publik merasa memiliki dan ikut terlibat secara langsung dan emosional dalam pesta demokrasi tersebut, pada akhirnya akan memangkas biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal tersebut.
***
Biaya politik yang tinggi seharusnya tidak perlu terjadi apabila partai politik mampu menjadi sebagaimana harusnya sebuah partai politik. Bukan sekedar halte persinggahan belaka, setelah mereka, para pemilik hajat memenuhi kebutuhannya, maka cita-cita ideologis partai pun ditinggalkan. Begitu juga dengan para elit. Jika ideologi memang tidak jauh berbeda mengapa harus membuat partai baru? Bukankah kesamaan ideologi adalah pengikat paling kuat dalam sebuah urusan politik.
Apa Reaksi Anda?