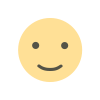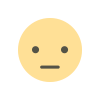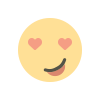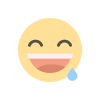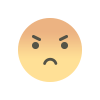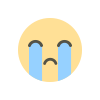POLITIK IDENTITAS: KENISCAYAAN DAN ANCAMAN
Temuan Indopol Survey and Consulting dalam surveiyang dilaksanakan pada 24 Juni–1 Juli 2023 yang lalu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa politik identitas di Indonesia tidak begitu populer dan tidak "disetujui" oleh publik, tetapi seringkali publik tidak pernah benar-benar menyadari bahwa mereka sedang terperangkap dalam politik identitas. Pernyataan bahwa “demokrasi tanpa politik identitas akan menjadi lebih baik”, tidak selamanya benar atau bisa jadi keliru sama sekali. Tantangan dan ancamannya bukan pada politik identitas itu sendiri, tetapi pada aktor-aktor politik yang menggunakan politik identitas untuk menghancurkan lawan politik dan bahan bakar kebencian demi kemenangan elektoral dan kekuasaan.
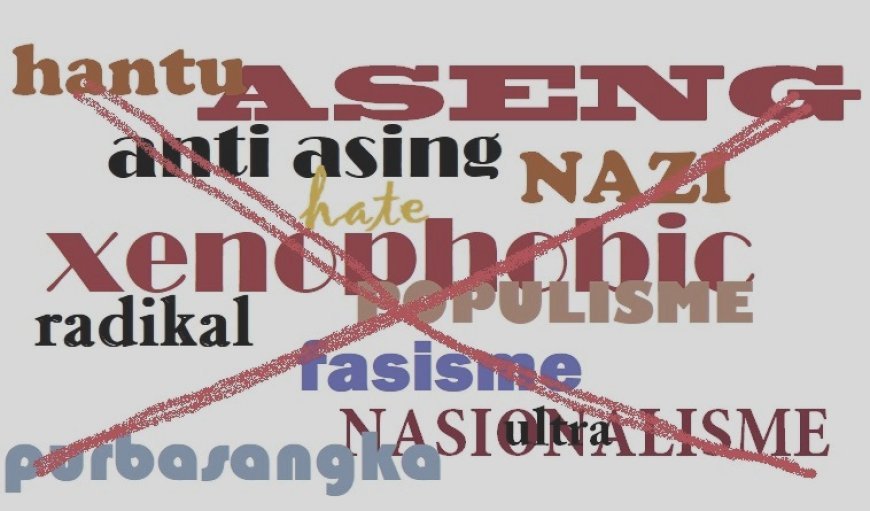
“Give dog a bad name and hang him,” demikian John Dewey (1950) menulis kalimat pertama dalam pengantar bukunya “Human Nature and Conduct”. Ia menyatakan bahwa sejak lama human nature adalah anjing bagi moralist profesional, yang melihat sifat dasar manusia dengan penuh kecurigaan dan rasa takut. Seperti itu jugalah selama ini kita melihat (dan nyatanya) politik identitas dalam kontestasi elektoral di Indonesia.
Politik Identitas di Indonesia
Dalam hal persepsi publik tentang politik identitas, menurut temuan Indopol Survey and Consulting dalam polling yang dilaksanakan pada 24 Juni–1 Juli 2023 yang lalu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa politik identitas di Indonesia tidak begitu populer dan tidak disetujui oleh publik, walau ada anggapan, bahwa publik tidak pernah benar-benar menyadari apabila mereka terperangkap dalam politik identitas. Semisal dalam melihat sosok pemimpin: opsi etnis/suku dan sentimen agama hanya dipilih responden masing-masing sebesar 0,73% dan 4,80%; alasan untuk memilih partai politik, opsi sentimen agama hanya dipilih responden sebesar 4,39%. Jika kita mengasumsikan bahwa publik yang setuju dengan politik identitas adalah mereka yang sangat fanatik dengan pilihannya, maka temuan survei juga menunjukkan bahwa mereka yang sangat fanatik dengan calon pemimpin politik tertentu, akan “Golput” jika jagoannya tidak bisa ikut berkontestasi, hanya 5,45%; jika calon pemimpin pilihannya ikut dalam kontestasi, opsi “akan memilih dan mendukung mati-matian” hanya diambil oleh 4,31% responden.
Sejak tragedi pada Pilkada DKI 2017, yang merupakan coreng hitam bagi demokrasi Indonesia, politik identitas telah menjadi patologi politik. Pada 2018, Freedom House juga menjadikan kasus penistaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (a.k.a. Ahok) sebagai faktor yang mengurangi skor “Freedom” Indonesia dari 65/100 pada tahun sebelumnya, menjadi 64/100 pada 2018. Fenomena politik identitas di Indonesia bukanlah unik, karena telah menjadi fenomena global.
Sejak masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, politik identitas di Indonesia mulai dianggap serius sebagai ancaman dan ancaman yang serius. Tragedi pada Pilkada DKI 2017 adalah sebuah coreng hitam bagi demokrasi Indonesia, di mana politik identitas telah menjadi patologi politik. Pada 2018, Freedom House juga menjadikan kasus penistaan agama terhadap Basuki Tjahaya Purnama (a.k.a. Ahok) sebagai faktor yang mengurangi skor “Freedom” Indonesia dari 65/100 pada tahun sebelumnya, menjadi 64/100 pada 2018. Fenomena politik identitas di Indonesia bukan unik, karena telah menjadi fenomena global.
Politik identitas dan saudara kembarnya populisme adalah dua entitas yang sangat menarik perhatian para akademisi di seluruh dunia, dianggap menakutkan dan ancaman bagi demokrasi. Namun begitu, politik identitas dan populisme sering disalahpahami sebagai sesuatu yang samasekali buruk. Seringkali, kelompok-kelompok yang menyebut politik identitas sebagai kejahatan, tidak benar-benar memahami apa politik idenititas sebenarnya.
Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah misalnya, sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar, adalah dua contoh terbaik bahwa tidak selamanya politik identitas itu menjadi buruk bagi demokrasi. NU dan Muhammadiyah adalah entitas penyokong, terlibat langsung dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, tokoh-tokoh seperti alamarhum Gus Dur dan Buya Syafii Maarif dapt dijadikan referensi untuk fakta tersebut. Begitu juga masyarakat marjinal semisal orang-orang Badui dan masyarakat adat Papua, malahan membutuhkan gerakan politik identitas agar mereka bisa terwakili atau mendapatkan tempat sewajarnya sebagaimana kelompok masyarakat adat lain di Indonesia. Affirmative action keterwakilan 30% perempuan di parlemen yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, juga mengharuskan 30% dari penyelenggara pemilu adalah perempuan. Pemberian perlakuan khusus pada kaum adat dan perempuan adalah bentuk “politik identitas” dijamin oleh konstitusi secara ajeg (UUD NRI 1945 pasal 28 H ayat (2 )).
Identitas Politik Identitas dan Populisme
Politik identitas adalah keniscayaan dan bukan fenomena baru. Ku Klux Klan (KKK) sebagai organisasi white supremacist pertama di Amerika Serikat (AS) telah ada sejak berakhirnya Perang Saudara AS di tahun 1865. Sebaliknya, National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) beridiri di 1909 hingga kini memperjuangkan persamaan hak di antara orang-orang kulit berwarna dan orang kulit putih terutama dalam hak pilih, dan penghapusan segregasi sosial di Selatan AS yang dilanda oleh teror KKK dan sentimen rasial yang mengerikan pada 1960-an. Salah satu tokoh NAACP adalah Justice Thurgood Marshall yang pada 1967, ditunjuk oleh Presiden Lyndon B. Johnson, sebagai hakim kulit hitam pertama di Mahkamah Agung AS.
Menurut Amy Gutmann (2003) dalam bukunya Identity in Democracy, politik identitas bisa membantu kerja-kerja demokrasi yang abai dilakukan pemerintah demi terwujudnya persamaan: a. civic equality, untuk mendapatkan peran yang sama dalam demokrasi dan pemerintahan; perlakuan yang sama sebagai warga negara, b. equal freedom atau hak warga negara untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan keyakinannya masing-masing dengan batas: kebebasannya tidak merenggut kebebasan orang lain, dan, c. basic opportunity, kesamaan hak dalam “the pursuit of happiness”. Politik identitas akan menjadi patologis apabila telah menghalang-halangi individu atau kelompok lain untuk memperjuangkan tiga hak mendasar di atas, atau secara umum, ketika politik identitas telah menjadi ancaman bagi individu atau kelompok lain untuk mendapatkan keadilan.
Dengan begitu, pernyataan bahwa “demokrasi tanpa politik identitas akan menjadi lebih baik”, tidak selamanya benar atau bisa jadi keliru sama sekali. Tantangan dan ancamannya bukan pada politik identitas itu sendiri, tetapi aktor-aktor politik yang menggunakan politik identitas untuk menghancurkan lawan politik dan bahan bakar kebencian demi kemenangan elektoral dan kekuasaan. Di sinilah populisme bermain sangat efektif dengan politik identitas. Meski tidak selalu harus berkonotasi negatif, karena perjuangan para founding fathers ini dahulunya juga menggunakan populisme sebagai konten, model dan ekspresi komunikasinya, populisme dan kaitannya dengan penggunaan politik identitas belakangan ini, sepertinya selalu cenderung menjadi kata yang profan (ingat baiamana Donald Trump menggunakan politik identitas di Pilpres AS 2016 dan 2020 yang lalu).
Sebagai ideologi tanpa akar (thin-centered ideology), yang menurut Cas Mude (2004) adalah ideologi yang mempertentangkan unsur rakyat (volonté générale yang dianggap pemilik kedaulatan utama), dan kelompok elit yang korup. Rakyat dan elit itu dapat disubsitusi dengan elemen-elemen yang berbeda, dalam konteks ke-Indonesiaan: pribumi dan aseng; rakyat dan oligarki; pekerja dalam negeri dan tenaga kerja China, dapat menjadi pengganti equivalen. Populisme sebagai ekspresi dan gaya komunikasi
Karenanya, meski tidak selalu patologis, politik identitas dan populisme harus diamati secara serius.
Ancaman Politik Identitas bagi Indonesia
Melihat temuan hasil survey Indopol tersebut, tidak serta merta membuat kita berhenti waspada. Populisme adalah ancaman bagi demokrasi global (Mackert, 2019), yang jika menemukan habitusnya maka akan segera memanfaatkan politik identitas sebagai elemen paling mendasar dalam konten kampanyenya. Kampanye yang sangat berorientasi kepada political market seperti saat ini (Winder et. al, 2011), menjadikan populisme sebagai pilihan logis bagi para politisi untuk memenangkan kontestasi elektoral. Penggunaan kata “rakyat” yang eksesif dapat mengarah pada nasionalisme yang berlebihan, dan menjadikan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan sebagai musuh dan jahat, beririsan dengan politik identitas yang patologis, isu-isu identitas akan sangat seksi. Politik identitas yang juga bisa diidentifikasi sebagai collective narcissism ideal dimobilisasi untuk menjadi pendukung ideologi populis
Oleh karenanya, meski akar politik identitas berdasarkan temuan survey Indopol hanya berkisar antara 4,5% -6% saja dari total penduduk, jika diambil angka moderar 5% saja, maka ada sekira 13 jutaan warga negara yang terimbas oleh politik identitas. Angka 5% itu menjadi luarbiasa apabila para pemimpin politik populis menjadikan politik identitas sebagai argumentem ad captandum; diseminasi kampanye yang sangat mudah dengan media sosial dan internet networking lainnya, politik identitas akan menjadi sangat berbahaya jika bisa memobilisasi pendukung dalam jumlah jutaan itu. Jika fenomena ini sudah meng-impede keadilan dan menghalang-halangi tiga hak mendasar tersebut di atas, maka politik identitas dan populisme bisa menjadi ancaman serius bagi hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Memori dua pilpres dan Pilkada DKI harus menjadi pengingat bagi kita, meski politik identitas bisa meningkatkan kualitas demokrasi, jika menjadi liar dan berkolaborasi dengan populisme, akan menjadi ancaman sanat serius bagi demokrasi liberal, lebih daripada itu, jika populisme mampu menjadikan konten-konten politik sebagai indetitas sosial/politik baru, secara mengerikan bisa menciptakan polarisasi yang menghancurkan tatanan kebangsaan. Dan jika begitu, kita hanya akan bisa berkata, “Acta Est Fabula, Plaudite..!”
Apa Reaksi Anda?