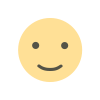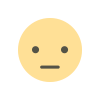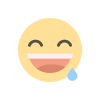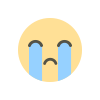Demokrasi Bukan Emansipasi Kutuk Mengutuk

Adaequatio intellectus nostri cum re. Konon, sekira dua ribu empat ratus tahun lalu, seorang filsuf melarikan diri dari Athena. Pelarian itu bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi menghindarkan Athena dari kutukan. Syahdan sebelum pelarian itu Aristoteles berkata: “Aku tak ingin membiarkan Athena membunuh filsuf terbaiknya untuk yang kedua kali…” Aristoteles merujuk pada kematian Socrates sekitar empar dekade sebelumnya. Bisa jadi, pelarian sang filsuf adalah pertanda bahwa Athena memasuki tahap akhir kejatuhannya.
Kematian Socrates barangkali harus menjadi tema paling awal yang mesti ditekuni seorang pelajar politik di kampus-kampus, maupun di kelas otodidak di mana borjuasi milenial yang kekiri-kirian menghirup kopi sambil membincangkan politik dan sesekali membuka lembaran buku berjudul, “The Last Days of Socrates”. Socrates menerima vonis mati oleh para “tiran demokratis”, dalam persidangan dramatis yang dikisahkan Plato dalam, Apologia, tetapi Socrates memilih menenggak hemlock (dalam Phaedo), daripada mati ditangan para tiran itu. “Pengutukan” Plato pada demokrasi melahirkan konstitusi utopisnya, “philosopher kings”.
Pembaca mungkin akan berkata: “Ah, topik ini sudah basi, tidak up to date dan sangat tidak relevan untuk diperbincangkan. Ini urusannya mahasiswa pemula yang sedang latah dengan filsafat!”
Dengan keberanian separuh matang dakwaan ini dibuat: “Sayangnya, itulah masalah terbesar saat ini. Saat diskursus demokrasi sudah terlalu ‘maju’, seakan melampaui batas-batas filosofisnya, telah dianggap sebagai ‘iman’ dan ‘doktrin’ sakral, undebatable dan undisputable.
Dan berseru: “Kita memiliki sistem politik terbaik bernama demokrasi dan gigit eratlah jangan sampai lepas, karena tanpa itu dunia kalian akan kiamat, imanilah sekuat nyawa dan yakinlah surga akan menanti kita, Hail Democracy.”
The system was taken for granted!
Emansipasi Kutuk Mengutuk. Brexit dan terpilihnya Donald Trump di 2016; kerusuhan di Bawaslu RI Mei 2019; “insurrection” di Gedung Capitol Amerika Serikat 6 Januari 2021; pemilu dan pilpres 2024 di Indonesia, pilpres Amerika Serikat dan “ancaman” Donald Trump; pasang naik Radikal Kanan di Eropa; permusuhan terhadap institusi-institusi formal menjadi tren global; bermunculan pakar-pakar karbitan mengutuk pakar-pakar “usang”; pemerintah dilabeli “dungu” karena tidak mendengarkan pendapat publik; isu kecil dan besar menjadi kudapan di media sosial.
Semua orang bisa menafsirkan apa saja sekehendak hatinya; pencarian kebenaran bukan lagi tugas ekslusif filsuf dan pakar. Segalanya menjadi kehendak individual. Jaqcues Derrida-pun akan sakit perut melihat semua orang memakai “deconstruction” secara serampangan tanpa disiplin hermeunetics sama sekali.
Dakwaan kedua hadir: ancaman terhadap demokrasi ternyata datang dari tubuh demokrasi itu sendiri, karena begitulah demokrasi, secara alamiah mengandung chaos. Beribu kali sayang, nature filosofis inilah yang sudah berhenti kita perbincangkan di saat demokrasi keluar dari bibir kita berjuta-juta kali sejak reformasi bergulir.
Publik diajak mendiskusikan politik tanpa pijakan filosofis dan berharap semua akan mengerti selayaknya seorang intelektual mengerti: demokrasi adalah pilihan terbaik; dalam konstitusi politik ini ada surga politik yang luarbiasa indah. Tetapi, setelah dua puluh lima tahun lebih berlalu, tidak seorangpun menemukan surga itu, maka kita mengutuk siapa saja yang layak dikutuk: elit, oligarki, pemerintah, orang kaya, orang asing, bahkan jika bisa bicara dengan bulan, kitapun akan mengutuknya karena membuat air laut pasang dan membuat Jakarta hampir tenggelam.
Sikap alergi kepada elit seakan pertanda seorang yang kritis. Padahal ruling class adalah keniscayaan, setidaknya begitu anggapan Gaetano Mosca dan Schumpeter. Demokrasi tidak operasional tanpa kelompok elit. Karena sejatinya, dengan pemilu rutin tersebut, kita setuju untuk mengirimkan lima ratusan orang untuk menjadi elit pembuat undang-undang (yang segera kita caci maki) di parlemen. Memilih satu orang untuk menjadi supreme elite, yang secara demokratis kita sebut sebagai presiden, lalu kita pelototi setiap jengkal kesalahannya, karena secara ironis pengutukan adalah salah satu nature demokrasi. Kutukan kepada siapa saja asal bukan kepada diri sendiri, dan demokrasi yang diagungkan itu.
Manusia post-modernist itu secara keliru menganggap diri progresif, menganggap modernitas sebagai antitesa kekunoan lalu menjadi kuno juga, dan mencari jati diri baru tetapi tidak kunjung ditemukan. Dalam pendidikan, setiap orang (tua) ingin mendapatkan hal yang paling mutakhir; dosen mencela mahasiswa yang mencantumkan referensi artikel dan buku tua; intelektual berlomba-lomba menggunakan kata “disrupsi”, media sosial dipakai secara masif agar tidak dianggap ‘jadul’; segala yang lama dikutuk tidak relevan; “classic” dianggap tidak cozy; sejarah menjadi guyonan youtuber; dan filsafat menjadi marjinal, dikunyah oleh manusia yang menganggap filsafat mestilah rumit dan membosankan. Tom Nichols ber-eulogi: “Para pakar telah mati!”.
Politik menjadi sangat ter-personalisasi, setiap orang membicarakan politik dan mantra-mantranya tanpa rujukan akademis atau memahami akar-akar keilmuannya yang panjang, dan membuat lompatan jauh dengan membicarakan demokrasi di hadapan publik. Mereka lupa atas kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada diri sendiri (dan publik) mengapa demokrasi harus dipilih.
Pilihan Terakhir. Begitulah, sesiapun yang terpelajar (benarkah?) akan yakin hanya demokrasi nan mampu menjamin “the pursuit of happines” itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jika (teleologi) Aristoteles masih layak diperbincangkan itulah tujuan kita bernegara: jaminan dan peluang bebas untuk mengejar kebahagiaan. Sayangnya “the idea of the good life” bukanlah konsep tunggal. Setiap orang, kelompok atau komunitas memiliki konsep yang berbeda tentang kebahagiaan. Sehingga akan muncul friksi dalam kelompok; friksi antar kelompok dalam komunitas, dan; antar komunitas dalam negara.
Kehendak-kehendak individu yang tak terbatas inilah yang membuat Plato dan Aristoteles merinding ketika demokrasi dijadikan konstitusi politik. Chaos mungkin sekali lahir dari “the idea of good life” yang beragam yang kemudian terakumulasi dalam kehendak massa; kekacauan dari ragam kehendak bebas yang menuntut keinginannya terkabulkan. Bisakah kita menyebut bahwa Marx memberikan solusi sejati pada demokrasi sejati: kediktatoran proletariat!
Apakah friksi-friksi sosial itu sebuah kejahatan atau benar-benar sebuah ancaman? Immanuel Kant menjawab, justru dengan adanya kontradiksi membuat individu-individu bisa bekerjasama di dalam satu kelompok atau komunitas. Menurut Kant, secara asali (Kant tidak pernah mengajukan konsep state of nature) kita adalah makhluk “unsocial sociability”. Manusia jika berkelompok selalu berpotensi besar untuk berkonflik. Tetapi manusia memiliki kesadaran, jika tidak bekerjasama dan berkompromi bencana akan datang. Sehingga bagi Kant, individualisme yang ditakutkan oleh Aristoteles dan Plato itu tidak begitu beralasan. Dalam komunitas kita bisa menentukan volonté générale (kehendak bersama), kata Rousseau. Kita adalah manusia-manusia tercerahkan. “Lo, we art the enlightenment creature.”
(Dengan lompatan pemikiran yang jauh): diskursus itu melahirkan demokrasi liberal yang kita anut saat ini. Sayangnya, “Masyarakat Sipil” (frase ini harus diperdebatkan) di Indonesia dalam gerak, nafas dan dialektikanya menghembuskan wewangian (atau busuk bagi kalangan tertentu) yang ambigu. Salah satunya: enggan mengakui diri sebagai Liberal, meskipun telah berhasil menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi liberal melalui beberapa amendemennya. Karena mengakui diri sebagai Liberal bisa berakibat sama dengan mengakui diri sebagai komunis. Senaif itulah dialektika publik kita, sehingga rela melepas label ideologinya karena takut stigma publik, tetapi berani berteriak sekencang mungkin terhadap ancaman (yang belum tentu datang).
Inilah beberapa konflik filosofis dalam memahami demokrasi. Mungkin karena, demokrasi seperti agama yang diturunkan dari orangtua, tanpa harus mempelajari terlebih dahulu, secara otomatis kita sudah menganut agama tertentu. Lebih untung lagi bagi mereka yang memiliki agama (menjadi ateis terlarang di negara Pancasila, tetapi dengan demokrasi Liberal, seorang ateis bisa menjadi selebritis) masih mendapatkan pencerahan paling kurang sekali sepekan: setiap Jumat atau di hari Minggu, misalnya. Tetapi diskursus demokrasi sangat diskursif, tidak tentu arah, dengan kurikulum sekehendak hati generasi “berteknologi tinggi” ini.
Apakah demokrasi (liberal) sudah mendekati masa akhirnya seperti yang konon diramalkan John Adams: demokrasi bisa kadaluarsa karena secara inheren memiliki chaotic nature. Barangkali kita saja yang terlalu sembrono menganggap demokrasi “sistem siap saji dengan merek dagang” sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Setiap usaha yang mengkritisi demokrasi selalu menghadapi doktrin iman yang sakral: demokrasi adalah yang terbaik. Siapa pula yang mau repot mengritik KFC, jika daging ayamnya sudah disajikan dengan rasa sempurna?
Akankah demokrasi menjadi distopia?
Meski keinginan untuk tidak berdemokrasipun adalah kehendak yang demokratis, namun setidaknya berdasarkan nature kewarasan, kita tidak ingin demokrasi liberal ini berakhir pada 2024 atau sepuluh atau dua puluh lima tahun lagi. Demokrasi mesti subur, tanpa harus ada arena antagonistik yang violence antara pendukung dan penista demokrasi. Karena sejatinya menistakan demokrasi sendiripun adalah demokratis, berdasarkan (nature) demokrasi itu sendiri. Sebagaimana menjadi bodoh adalah pilihan demokratis, selagi kebebasan untuk menjadi bodoh itu tidak menghalangi orang lain untuk memiliki kecerdasan.
Acta est fabula..! Tidak ada jalan lain kiranya, jika itu yang kita kehendaki, maka diskursus politik itu harus dicerdaskan, pendidikan politik seperempat matang akan melahirkan generasi pemarah, pengutuk dan pencela, yang dengan suka ria difasilitasi oleh cozy reality media sosial yang memabukkan. Mengembalikan kewaspadaan kita kepada terhadap “chaotic nature” demokrasi juga tidak terlalu salah, karena demokrasi itu memang bukan sesuatu yang mati, demokrasi adalah konstitusi politik paling dinamis. Meski kita perlu juga waspada.
Tidak ada yang bisa menghentikan “kehendak massa” kecuali kediktatoran!
Jika demokrasi sebagai konstitusi politik adalah pilihan terakhir (bukan yang terbaik), tidakkah seharusnya dengan kepala yang dingin, dengan dialektika yang bernas kita memahami ulang demokrasi dengan rujukan-rujukan yang lebih “tinggi”, daripada sekedar berteriak-teriak mengutuk dan mencela, menyuburkan paranoia dan akhirnya unsocial sociability itu menjadi berkarat karena terlalu sering kita jemur di tengah panas dan hujan, karena kita lebih suka menggunakan urat leher yang mengeras dan aspal jalanan sebagai bukti perjuangan?
Apa Reaksi Anda?